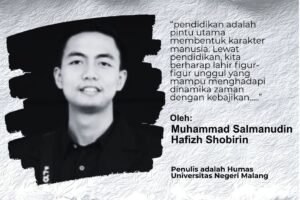Oleh: Dahlan Iskan
BARU di Pemilu ke-4 di masa Pak Harto saya ikut nyoblos. Tiga Pemilu sebelumnya saya selalu Golput –istilah yang dipopulerkan oleh Arief Budiman sebagai gerakan anti Pemilu yang pemenangnya sudah diatur.
Di Pemilu ke-4 itu, 1987, saya pun sebenarnya ingin Golput lagi. Karena itu saya tidak mendaftar sebagai pemilih. Ketika daftar nama pemilih sementara diumumkan tidak ada nama saya. Pun ketika daftar pemilih tetap diumumkan.
Tiba-tiba saya dipanggil Pak Moh Said, ketua DPD Golkar Jatim yang legendaris. Ia kolonel TNI-AD. Pejuang kemerdekaan. Selalu merokok pakai pipa. Orangnya sederhana tapi berwibawa. Tinggi. Besar. Selalu serius. Beliau orang intelijen.
”Ada apa ya?” tanya saya pada diri sendiri.
Di masa sebelumnya saya punya pengalaman pahit dengan beliau. Saya pernah dimarahi habis-habisan. Empat mata. Di salah satu kantornya di Taman Chandra Wilwatikta, Pandaan.
Belum ada jalan tol menuju Pandaan. Saya harus datang menghadap beliau –di jarak 50 km dari kantor Jawa Pos Surabaya.
Jawa Pos dinilai anti-Golkar. Saya harus mempertanggungjawabkannya.
Menghadapi orang Jawa seperti beliau saya tahu cara bersikap yang terbaik: diam. Tidak membantah. Tidak perlu menjelaskan. Diam. Dengarkan sungguh-sungguh. Pasang mimik pasrah. Jangan muka acuh atau merengut.
Begitu pula ketika saya pernah dimarahi Gus Dur di Istana Presiden. Soal Jawa Pos juga.
Pun saat saya dimarahi Presiden SBY. Soal mengapa saya mengangkat dirut Bank Mandiri tanpa konsultasi.
Beliau marah lewat telepon. Panjang. Saya dengarkan sungguh-sungguh. Sama sekali tidak memotong pembicaraan beliau. Saya memang merasa bersalah: kok seberani itu. Saya tidak perlu menjelaskan mengapa sikap itu saya ambil. Biarlah beliau marah. Beliau memang berhak marah. Wajar sekali.
Sampai sekarang pun saya belum punya kesempatan menjelaskan latar belakang keputusan saya waktu itu. Yang jelas pilihan saya tersebut sangat tepat. Sampai sekarang mantan dirut itu masih tetap jadi orang hebat. Jadi menteri yang penuh prestasi.
Dalam menghadapi marahnya Pak Said tadi saya juga diam. Tidak berusaha menjelaskan mengapa koran perlu bersikap independen. Saat itu pun independen dianggap anti Golkar.
Saya terus saja mendengarkan kemarahan beliau. Pak Said tahu bahwa saya mendengarkan sungguh-sungguh. Saya sudah bertekad: berapa jam pun dimarahi akan tetap diam-pasrah seperti itu.
Terakhir Pak Said sampai pada puncaknya: mengancam akan menutup Jawa Pos. Ia bisa melakukan itu.
Saya tidak menunjukkan ekspresi kaget atau menantang. Beliau terus berkata-kata mengenai kekuasaan yang beliau miliki. Saya tetap diam. Maka beliau tegaskan: Jawa Pos akan ditutup.
Setelah kata itu diucapkan, saya baru minta izin bicara. Pakai bahasa Jawa halus. ”Kalau Jawa Pos memang akan ditutup, saya pasrah. Setelah itu saya nganggur. Saya akan ikut kerja di Pak Said,” kata saya lirih, sambil menunduk.
Beliau diam agak lama. Lalu berdiri. ”Ya sudah, boleh pulang,” ujar beliau.
Saya pun menyalami tangan beliau dan menciumnya.
Saya pasrah apa yang akan terjadi. Saya tidak ceritakan pertemuan itu ke redaksi dan wartawan. Saya khawatir akan memengaruhi independensi mereka.
Yang jelas, setelah itu,.Jawa Pos baik-baik saja.
Menjelang Pemilu berikutnya saya dipanggil ke Progo 5. Itulah rumah Pak Said: di jalan Progo No 5 Surabaya. Itu sudah jadi rumah politik. Siapa saja yang ingin jadi apa saja harus sowan ke Progo.
”Ada apa ya?” tanya saya lagi ke diri sendiri. Saya pasrah saja. Saya pun melangkah masuk ke Progo. Sudah ada dua-tiga orang di sana.
”Dik Dahlan kami calonkan sebagai anggota MPR dari unsur Golongan,” ujar beliau. Saya kaget. Saya? Anggota MPR? Dari Golkar?
Tidak ada kata menolak.
Ya sudah.
Tapi ada kesulitan besar. Seorang calon anggota MPR harus terdaftar sebagai pemilih. Itu harus dibuktikan dengan tercantum di daftar pemilih tetap. Padahal nama saya tidak ada di sana.
”Tidak ada di daftar? Tidak mendaftar?” tanya staf sekretariat terheran-heran.
Mereka pun saling berbisik. Ini sudah putusan Pak Said. Beliau itu idu geni –ludah api. Kata-katanya harus terlaksana.
”Ya sudah. Akan kami atur,” kata staf sekretariat tersebut.
Beberapa hari kemudian saya harus menandatangani beberapa dokumen. Saya dianggap tercantum di daftar pemilih tetap di salah satu daerah di Madura. Lalu ada dokumen mutasi: tempat mencoblos di salah satu TPS di Surabaya.
Di hari pelaksanaan Pemilu saya dapat surat mutasi itu: bisa saya pakai mencoblos Golkar di TPS Tenggilis Mejoyo Surabaya.
Sejak itu saya selalu mencoblos di setiap Pemilu. Pun hari ini. Tadi malam saya paksakan pulang ke Surabaya: demi pilih nomor….Anda sudah tahu. (*)