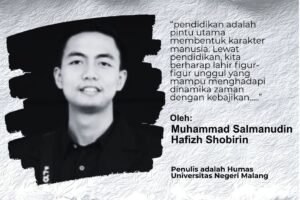Masih hangat di ingatan, sepak terjang pemusnahan korupsi di Indonesia. Namun, harapan tersebut kini ternodai dengan tindakan biadab ala tikus korporat dalam laju pemerintahan. Indonesia pun berduka, sosok panutan dalam kehidupan bernegara lagi dan lagi terjegal urusan korupsi. Di tahun 2020, ICW menyebutkan bahwa sepanjang semester I korupsi yang terdata secara resmi sebanyak 169 kasus. Narasi ini bukan arahan untuk membantai tindakan seseorang secara personal. Hanya saja perlu dibuat sebagai bahan renungan. Sampai kapan para intelektual peradaban terjegal arus korupsi ini? Tidak cukupkah 75 tahun merdeka untuk menuntaskannya?
Merujuk tentang pembahasan korupsi yang karut marut di negeri, memang dibutuhkan kajian dan analisis yang tajam. Darimana, motifnya apa, dengan siapa, bahkan sampai mengapa dan juga hal kompleks lainnya. Namun, semoga narasi sederhana ini dapat menjadi pemantik diskusi antar pemikiran untuk segera dipecahkan. Apakah benar, ini kesalahan pribadi? Kalaulah hanya kesalahan pribadi, lantas mengapa terjadi secara massal? Bukankah seorang manusia bisa belajar dari sebuah kesalahan, kemudian memantapkan diri dalam kebaikan. Bahkan, seharusnya seorang citizen memahami bahwa biaya yang dibayarkan kepada negara adalah hak tiap individu yang berhak. Hal ini sudah tersampaikan dengan jelas lewat dasar negara yang kita anut pada sila ke 5 yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Lantas, mengapa sampai hati ikut memakan harta yang bukan miliknya? Mirisnya, para pemakan uang milayaran ini kebanyakan bukan lulusan tamatan SD atau SMP, sebagian besar tersorot lulusan sarjana bahkan sekelas magister. Mendapatkan jabatan yang tak biasa, bahkan dihormati bak para ulama.
Di sisi lain, faktor pendukung korupsi banyak terjadi. Mulai dari tuntutan gaya hidup glamour, kehidupan hedonisme, dan foya – foya. Semua ini juga menjadi pendukung korupsi. Di skala kecil, coba kita ingat sewaktu masih kanak – kanak. Korupsi memang sudah menjadi hal biasa dalam kehidupan sehari – hari. Korupsi waktu, dana anggaran lembaga sekolah maupun kampus. Sehingga, korupsi yang terjadi sudah lama diterapkan lewat lingkungan sehari – hari. Maka tidak heran, ketika menginjak dewasa, banyak dari sebagian generasi terseret arus tersebut. Cakupan korupsi yang dilakukan luas, tidak hanya terbatas pada waktu saja. Bahkan dana haji, infrastruktur, bantuan sosial pun bisa menjadi target. Maka ini yang perlu disadari, eksistensi korupsi bukan hanya bentuk dari kecelakaan pemahaman pribadi, melainkan terwadahi menjadi sebuah tradisi yang diturunkan antar generasi. Di sisi lain, sudah menjadi rahasia umum bahwa biaya kontestasi politik dinilai sangat tinggi, sehingga membutuhkan modal yang super mewah. Hal ini juga disoroti sebagai cikal bakal pertumbuhan korupsi di tengah jabatan pemerintahan yang notabene diidolakan. Tak tanggung – tanggung, dalam Kabinet baru Jokowi – Ma’ruf sudah 5 menteri tertangkap melalui OTT (Operasi Tangkap Tangan).
Lantas, apa penyebab yang demikian bisa terjadi bahkan diteruskan antar generasi? Kunci pertama yang perlu disoroti yakni adalah pemahaman manusia era sekarang terkait korupsi. Seperti yang sudah diketahui bersama, bahwa dalam memulai sebuah tindakan manusia harus memiliki sebuah pemikiran, pengalaman dan dukungan dari informasi yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Robert Morrison dalam bukunya yang berjudul Sociology : Its Structure and Change mengutip pernyataan dari seorang Max Weber terkait teori aksi. Max berpendapat bahwa seorang individu melakukan suatu tindakan berdasarkan atas pengalaman, persepsi, pemahaman dan penafsirannya atas suatu obyek stimulus atau situasi tertentu.
Kemudian, teori inipun dapat dengan mudah dipahami dengan sempurna jika merujuk pada pernyataan Syaikh Taqiyuddin An Nabhani dalam kitab At-Tafkir ( diterjemahkan menjadi buku Hakikat Berfikir) yang menyampaikan bahwa tindakan seseorang berdasarkan pemahaman yang dimiliki. Secara sederhana, jika manusia mengambil langkah untuk bertindak dan melakukan korupsi, maka sudah dipastikan terdapat pengalaman, persepsi, serta pemahaman yang melegitimasi kebolehan akan tindakan kriminal ini. Walaupun terdapat kemungkinan untuk memikirkan resiko dan dampak yang dihasilkan.
Jika ditilik lebih lanjut, fitrah untuk bersikap serakah pasti ada dalam setiap manusia. Namun, hal ini akan menjadi permasalahan bila nafsu keserakahan dibiarkan membabi buta menuruti akal manusia. Kondisi semacam inilah yang sekarang tengah menjadi pola pikir kebanyakan masyarakat. Bahwa sejatinya, mereka yang dianggap sebagai manusia sempurna adalah mereka yang bergelimang harta. Bahkan hal inipun juga tercetak jelas dalam arah pendidikan bangsa yang disederhanakan *lulus kuliah untuk kerja*. Memang, tidak bisa dipermasalahkan seutuhnya jargon demikian. Hanya saja, yang banyak tak diketahui dalam slogan ini, yakni di sisi mana keberkahan diutamakan. Karena ketiadaan pernyataan bahwa keberkahan itu penting, maka dapat dipastikan cara apapun akan ditempuh asal harta diraih. Belum lagi kondisi biaya politik yang tinggi menjadikan banyak kandidat harus memiliki modal yang super untuk sangu. Gaya hidup hedonisme, mobil mewah beserta uang puluhan juta menjadi suatu tuntutan yang harus dilengkapi. Menjadi hal yang langka memiliki jabatan tinggi tanpa jas dan dasi.
Belum lagi, dari sisi masyarakat seakan mengamini kehidupan ala sekuleristik sekarang. Selain korupsi yang terjadi di tingkatan penggelapan uang negara, nyatanya yang terjadi di lingkungan masyarakat juga tidak jauh beda. Mulai dari korupsi tingkat desa, antar komunitas, sampai desa. Banyak alasan mengapa korupsi tersebut dilakukan. Bahkan banyak slogan beredar *daripada uangnya kemakan si dia, alangkah baiknya aku ambil jatah*. Alih – alih tuntas, malah merajalela.
Sedangkan dari sisi kenegaraan, tampaknya jeratan hukum yang diberikan masih belum memberikan jera bagi terpidana dan orang diluaran sana. Banyak didapati fakta para pidana korupsi hidup berkecukupan dan mewah selama ditahanan. Semakin kaya, semakin tinggi pula fasilitas tahanan yang bisa dibeli. Di sisi lain, sudah menjadi rahasia umum bahwa tindakan ini bisa dilakukan secara massif. Artinya, bila satu orang tertangkap, masih ada teman lain yang akan melanjutkan kerja korupsi.
Inilah rupa kehidupan yang dijalani sebagai perwujudan dari sistem demokrasi. Bahkan seorang Prof. Mahfud M.D. menyampaikan bahwa seseorang yang masuk dalam sistem pemerintahan demokrasi, maka dia akan menjadi iblis. Nampaknya, pernyataan ini sudah terlihat sangat nyata. Bagaimana seorang kader dengan semangat awal memperjuangkan perubahan, tapi bila masuk ke dalam sistem pemerintahan berbalik menjadi seorang yang diam dan terpaksa bahkan sukarela sepakat dengan kedzaliman. Wajar bila yang terjadi demikian. Bagaimanapun juga, demokrasi tetaplah sistem buruk yang paling baik untuk diterapkan. Alih – alih khawatir dipimpin dengan era kediktatoran, demokrasi hadir dengan menawarkan kedaulatan dari, oleh, dan untuk rakyat. Rakyatnya sendiri belum menyadari bahwa frasa kedaulatan untuk rakyat hanya berlaku mutlak bagi para kaum oligarki. Sulit memang untuk meyakini, karena telah berpuluh tahun kita hidup dalam keindahan semu demokrasi.
Sejatinya, apa yang berusaha ditanamkan pada masyarakat hari ini yakni materi alias keuntungan adalah hal utama yang dicari. Maka tak heran, bahkan cara haram sekalipun akan ditempuh demi terwujudnya keberlimpahan harta. Bayangkan, jika pola pikir keuntungan dan keserakahan akan materi menjadi sesuatu yang harus dipuja, mau tak mau kehancuran akan segera tiba. Pasalnya, sebuah peradaban gemilang tak dapat dibendung dalam waktu yang lama dengan dasar keserakahan. Alih – alih menyejahterahkan, malah yang terjadi kaum marjinal semakin terpinggirkan. Jurangan antara si miskin dan si kaya semakin nyata. Bahkan, kondisi penerapan akan sistem demokrasi telah merongrong karakter kebaikan pada diri manusia. Intelektual peradaban yang notabene penggerak perubahan, malah menjadi kaki tangan penjajahan gaya baru. Korupsi hanya satu dari sekian kriminalitas yang dibendung dalam balutan demokrasi-kapitalisme.
Degradasi moral, gaya kehidupan liberal, hedonisme menjadi lanjutan dari dampak penerapannya. Lalu bagaimana untuk memperbaiki kerusakan massal ini? Jelas bukan kembali kepada penerapan ideal demokrasi. walaupun diterapkan seideal mungkin, bentuk kedaulatan yang mutlak di tangan oligarki tak akan berpindah pada keseluruhan masyarakat apalagi kaum marjinal. Butuh sistem yang mampu memberikan keadilan bagi si kaya dan si miskin agar tak saling merasa cemburu karena penerapan kebijakannya. Bukan berarti dunia harus diubah menjadi sama rasa sama rasa, karena adil literally tidak harus sama. Frasa penempatan adil harus diukur kadarnya.
Bukan berarti juga melirik pada penerapan ala kediktatoran, karena sejatinya ada sistem peradaban yang mampu mewujudkan bagi kesejahteraan umat manusia secara hakiki. Meniadakan benih kedzaliman, menumpuk benih kebaikan dari segala penerapannya. Reza Pankhurst dalam bukunya The Inevitable Calliphate mengungkap bahwa keidealan tata kelola negara dapat diwujudkan dengan penerapan Islam secara totalitas. Hal inipun didukung dengan apa yang ada dalam buku The Great of Civilization karangan Will Durant. Walaupun memang agak sulit meyakini bahwa agama bisa disandingkan dengan perpolitikan. Kenyataannya, terdapat fakta yang tak terbantahkan, bahwa dalam kurun waktu 1400 tahun lamanya Islam pernah berdiri sebagai suatu bangunan pradaban yang kokoh dan memimpin dunia dari segi kemiliteran dan perpolitikan.

Penulis : Nor Rahma Sukowati., S.Pd. ( Guru di Sidoarjo )