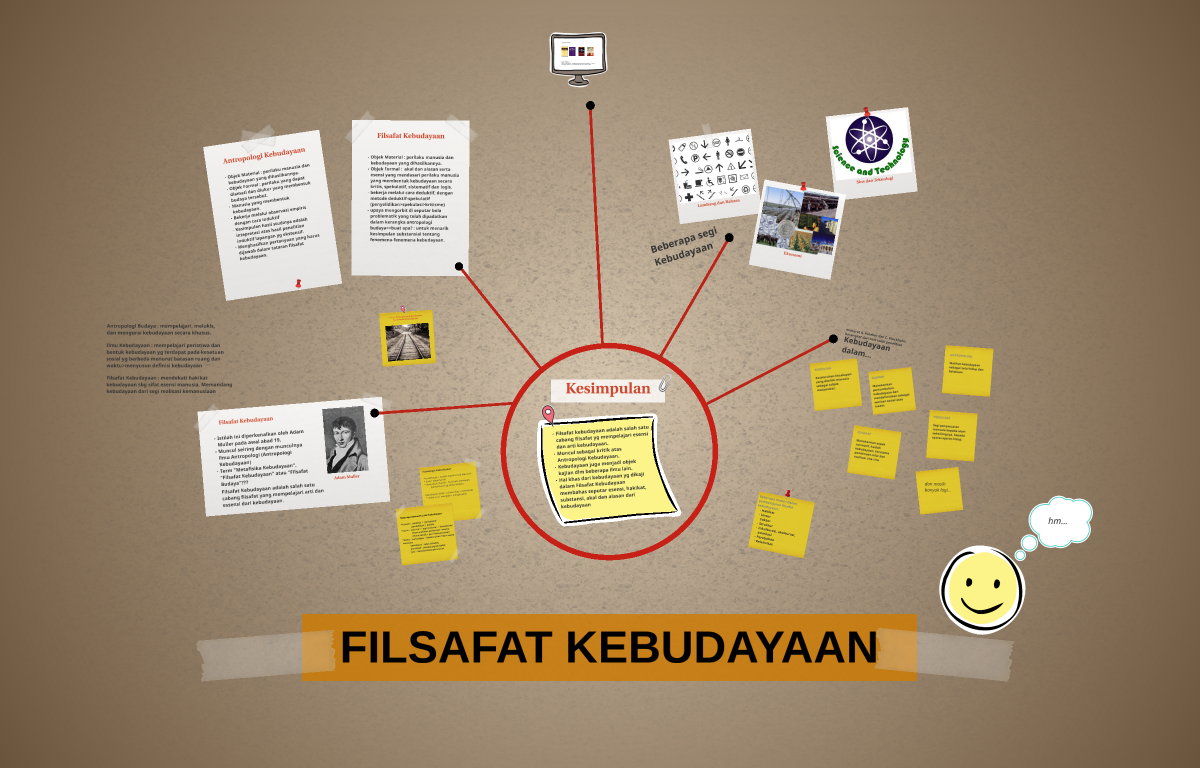
Filsafat Kebudayaan
Sebagai petualangan intelektual, berfilsafat menjadi sesuatu yang niscaya bagi setiap individu. Hal ini telah penulis uraikan dalam tulisan sebelumnya, Berfilsafat adalah Petualangan Intelektual” (https://baliportalnews.com/2021/02/berfilsafat-adalah-petualangan-intelektual/), yang dengan ketat menjelaskan bahwa filsafat adalah aktivitas berpikir yang kritis menuju sebuah ‘kejernihan’, kejernihan berpikir dan merefleksikan tentang ‘sesuatu’.
Sejurus dengan itu, dalam sejarah perkembangannya, filsafat lahir sebagai kritik atas mitos dan mitologi. Menjadi sebuah kritik, karena di jamannya, para filsuf Yunani Kuno, memandang bahwa mitos dan mitologi tidak lagi ampuh untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang hakikat realitas, dan juga prinsip dasar realitas. Secara sederhana mitos dapat dikatakan sebagai kisah atau cerita tentang asal usul dunia, alam semesta dan manusia yang berasal dari para dewa. Selian itu, mitos juga berarti kisah tentang pekerjaan dewa-dewa dalam kehidupan dunia manusia dan alam semesta. Dari sini, dapatlah dikatakan bahwa mitos dapat dipakai untuk menyatakan apa yang tidak dapat hadir secara kelihatan. (https://www.ancient.eu/mythology/).
Tampak jelas bahwa upaya ‘para filsuf’ Yunani Kuno dijamannya, terutama dalam mempertanyakan realitas dan prinsip dasar realitas, mitos-mitologi tidak lagi memadai, maka akhirnya mereka bergeser ke logos, untuk menjawab prinsip dasar realitas. Dengan itu, mereka pun menaruh perhatian pada akal budi (logos), karena diyakini hal itu lebih tinggi dibandingkan mitos-mitologi. Dengan akal budi, segala kejadian alam semesta (realitas) dapat dijelaskan.
Pendek kata, filsafat tidak bisa dilepaskan dari budaya. Kendati tulisan ini bukan semata karena proses lahirnya filsafat itu adalah terjadi di dalam kebudayaan tertentu (budaya Yunani Kuno), tapi terutama mau menguraikan bahwa filsafat merupakan upaya rasional untuk melihat dan merefleksikan realitas, termasuk upaya memaksimalkan ‘logos’ untuk mencari jawaban atas sebuah kondisi dalam realitas.
Melampaui itu, filsafat amat berhubungan dengan filsafat. Mengapat? Karena filsafat diyakini bisa membantu budaya untuk merenungkan nilai-nilai dan makna yang ada, kemudian melihat secara jeli dan benar-benar otentik suatu kebudayaan yang dimiliki manusia itu. Filsafat juga bisa memberi dorongan bagi manusia untuk mengkritisi realitas budaya dan peradaban, serta memberi nuansa kritis bagi model dan cara pengembangan budaya ke arah yang lebih baik.
Fakta kini mementaskan sebuah fakta bahwa di dalam pengembangan kebudayaan, telah banyak hal yang dilakukan manusia, dan masih terdapat banyak hal lain lagi, yang bisa dilakukan terkait bagaimana budaya itu bisa dimajukan. Maka untuk bisa masuk dan menunjukkan dengan jelas dna ketat bahwa sebuah kebudayaan terkait erat dengan filsafat, perlu juga diuraikan apa itu kebudayaan. Secara sederhana kebudayaan dapat dimengerti sebagai endapan dari kegiatan dan karya manusia. Kebudayaan merupakan manifestasi kehidupan manusia. Manusia selalu mengubah alam melalui kegiatan hidupnya. (bdk. van Peursen 1976: 11). Kebudayaan yang sedemikian dekat dengan kehidupan manusia, serta selalu mengubah kehidupan manusia, karena kebudayaan erat terkait dengan berbagai fenomena yang muncul di setiap saat dalam kehidupan manusia.
Jadi secara jelas pula dapat penulis katakan bahwa filsafat dan budaya berkaitan erat. Kaitan erat keduanyaa tampak lewat sebuah kenyataan bahwa filsafat membantu mempertajam budaya. Penerapan prinsip-prinsip filosofis pun menegaskan hubungan erat antara keduanya, karena di dalamnya terdapat sikap kritis, konsistensi, logika berpikir, serta kemampuan untuk ‘bertolak ke kedalaman’. Demikianlah dengan filsafat, kita bisa memahami budaya dengan totalitas, serta dengan penuh kreatif membaca arah kebudayaan yang kita hadapi dan hidupi.
Sedemikian penting filsafat itu dalam mendekati sebuah kebudayaan, juga karena harus diakui bahwa kebudayaan kini, dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Bahkan bukan tidak mungkin manusia akan terasing dengan budayanya, karena pesatnya perkembangan realitas tadi. Namun keuntungannya adalah ketika kita berada di tengah perkembangan pesat tersebut, manusia yang sudah ada di era modern kini tentu dengan kesadarannya memiliki kepekaan yang mendorongnya secara kritis untuk menilai kebudayaan yang sedang berlangsung serta perkembangannya.
Sugiharto (2015: 1), menyatakan bahwa dalam panggung global saat ini, budaya akan ‘menenun dan merombak’ jaringan konseptual yang kaku, secara terus menerus. Panggung budaya dunia saat ini adalah percakapan yang tidak pernah berakhir, di mana tradisi tidak hanya diartikulasikan kembali, tetapi juga diciptakan kembali, dan diperluas ke potensi yang tidak dapat diprediksi dalam konteks dunia baru. Budaya hidup dalam hubungannya dengan tata bahasa percakapan kita yang terjadi dalam realitas kini. Fakta ini menegaskan bahwa dampak dari perkembangan peradabanlah yang menyebabkan kita butuh sebuah cara dan konsep berpikir yang kritis. Maka dari itu, filsafat begitu dibutuhkan.
Hemat penulis, berpikir dengan kritis, logis dan komperehensif menjadi kunci. Bahkan menurut ukuran tertentu, manusia yang memiliki akal budi, daya nalar, serta kesadaran kritis akan berbagai perkembangan realitas, bisa dijamin akan mampu menyesuaikan diri dengan kebudayaan itu.
Budaya pasti akan terus berkembang, namun kemampuan berpikir manusia (logos) yang identik dengan filsafat itu, akan juga mendorong manusia untuk bisa membacanya dengan kritis demi pengembangan dan pemajuan kebudayaan ke depan.
Akhirnya, upaya-upaya pemajuan kebudayaan saat ini, perlu dan penting untuk berpijak dari cara berpikir filsofis, sebagaimana telah diuraikan di atas. Kita tidak perlu mengelak bahwa saat ini, kita membutuhkan cara berpikir itu, bukan terutama untuk mengkritisi secara ‘membabibuta’ kebudayaan atau merombak dengan massif berbagai kebudayaan yang telah hidup itu atau bahkan menentang tradisi budaya yang sudah lama hidup, tetapi justru berpikir bahwa dengan cara kritis dan logis, kita bisa melihat dunia, melihat gejala kehidupan dan melihat budaya itu.

Penulis: Ambrosius M. Loho, M. Fil. (Dosen Universitas Katolik De La Salle Manado, Pegiat Filsafat).












Pegiat yang bukan hanya sebagai penikmat namun juga sebagai motivator bagi para pemula untuk ‘benar-brnar’ memulai. 🙏