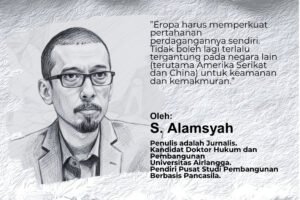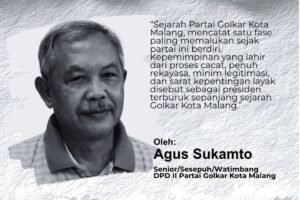KETIKA sebuah daerah wisata sedang naik daun, sering muncul keyakinan bahwa pertumbuhan akan berlangsung selamanya. Bali dan Thailand membuktikan bahwa anggapan tersebut keliru. Dua ikon pariwisata Asia Tenggara itu kini menghadapi tekanan serius akibat tata kelola yang lemah dan pembangunan yang melampaui daya dukung lingkungan. Malang Raya perlu belajar sebelum terlambat.
Fenomena “Bali sepi” pada periode Tahun Baru 2025/2026 menjadi contoh nyata. Data Bandara Ngurah Rai mencatat lebih dari 1,48 juta pergerakan penumpang selama libur akhir tahun, meningkat sekitar 9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sepanjang 2025, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali juga mencapai hampir 7 juta orang.
Namun, lonjakan tersebut tidak sejalan dengan kondisi industri. Tingkat hunian hotel berbintang justru tertahan di kisaran 70–80 persen. Di beberapa wilayah, penurunan okupansi mencapai 15 persen. Penyebab utamanya adalah kelebihan pasokan vila dan homestay, termasuk yang tidak sepenuhnya mematuhi tata ruang, sehingga memicu perang harga dan menurunkan kualitas layanan.
Masalah infrastruktur turut memperparah keadaan. Kemacetan, persoalan sampah, dan krisis air bersih menurunkan kenyamanan wisatawan. Banyak pengunjung tetap datang, tetapi memilih tinggal lebih singkat dan membelanjakan uangnya secara lebih hemat. Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah juga berdampak besar. Sepanjang 2025, sekitar 750 kegiatan MICE dibatalkan dengan potensi kerugian mencapai Rp 3,15 triliun.
Thailand mengalami situasi serupa. Pada 2025, jumlah wisatawan turun menjadi 32,97 juta orang atau merosot 7,23 persen. Pasar Tiongkok anjlok lebih dari 33 persen akibat krisis keamanan. Penguatan mata uang Baht serta kenaikan biaya hidup semakin menggerus daya saing negara tersebut. Polusi udara dan kerusakan terumbu karang memperburuk citra destinasi.
Pengalaman Bali dan Thailand menunjukkan bahwa popularitas tidak selalu berarti keberlanjutan. Status sebagai destinasi unggulan tidak otomatis melindungi dari krisis jika tata kelola diabaikan.
Malang Raya saat ini berada dalam fase pertumbuhan pesat. Investasi meningkat, hotel dan vila baru bermunculan, serta kunjungan wisata terus bertambah. Kawasan ini menjadi salah satu motor pariwisata Jawa Timur. Namun, Malang Raya juga memiliki kerentanan geografis yang tinggi. Lereng pegunungan, daerah tangkapan air, dan lahan pertanian produktif tidak dirancang untuk pembangunan masif tanpa batas.
Pengalaman kawasan Puncak dan Bandung Selatan menunjukkan bahwa kerusakan wilayah hulu hampir selalu berujung pada bencana di hilir. Deforestasi dan alih fungsi lahan menghilangkan fungsi resapan air. Jika hal ini terjadi di Malang Raya, dampaknya tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga pada keberlangsungan pariwisata.
Bahaya terbesar justru muncul ketika sebuah destinasi sedang berjaya. Saat okupansi tinggi dan investasi mengalir, muncul anggapan bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal, oversupply, eksploitasi air tanah, dan degradasi lingkungan sedang menumpuk secara perlahan.
Agar tidak mengulang luka yang sama, Malang Raya perlu memperkuat kebijakan keberlanjutan. Pengetatan tata ruang, pembatasan daya dukung wisata, selektivitas investasi, serta penerapan standar pariwisata hijau harus menjadi prioritas. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media juga perlu diperkuat.
Bali telah kehilangan triliunan rupiah akibat dislokasi industri. Thailand kehilangan jutaan wisatawan karena krisis berlapis. Semua itu terjadi bukan karena kekurangan potensi, melainkan karena terlambat membenahi tata kelola.
Malang Raya masih memiliki waktu untuk belajar. Namun waktu ini tidak akan menunggu. Euforia pariwisata hari ini tidak menjamin keberlanjutan esok hari. Justru saat sedang berjaya, disiplin kebijakan harus diperkuat.
Pariwisata yang sehat bukan yang paling ramai, melainkan yang paling mampu menjaga keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. (***)