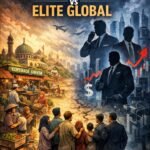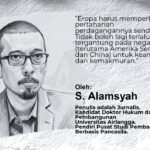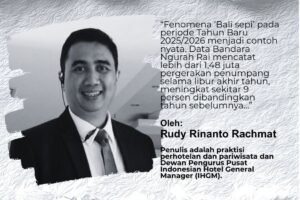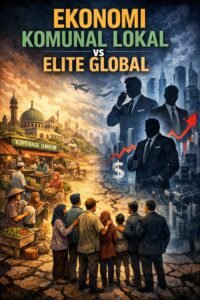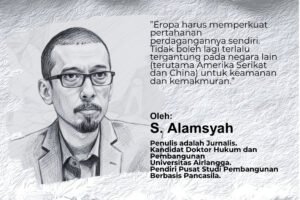Oleh: Hamim Pou
Suatu pagi di pesisir Bone, nelayan kecil bernama Rahman menepikan perahunya. Perairan luas di timur Gorontalo itu masih kaya ikan segar: cakalang, tongkol, sampai tuna. Tapi harga di pasar kerap tak berpihak padanya. “Kalau saja ada yang beli pasti, harga wajar, kami bisa hidup tenang,” katanya suatu kali.
Tak jauh dari sana, di Tapa, petani sayur memetik kangkung, bayam, wortel, kacang panjang—bahkan sebagian mulai beralih ke organik. Di Kabila, sawah seluas ribuan hektare dipanen tiga kali setahun. Padi, sayur, ikan—semua tersedia di Bone Bolango. Tapi keluhan yang sama terdengar: pasar tidak pasti, harga jatuh saat panen raya, modal tercekik.
Bayangkan bila Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir dengan pola belanja yang memihak mereka: kontrak panen untuk petani padi, kontrak sayur untuk kebun Tapa, kontrak ikan untuk nelayan pesisir. Harga stabil, pasar pasti, pembayaran cepat. Bukan hanya perut anak-anak sekolah yang kenyang, tapi pendapatan petani dan nelayan ikut naik.
Inilah harapan yang sebenarnya sangat sederhana: agar program triliunan rupiah tidak berakhir di kontraktor besar di kota, melainkan benar-benar berdenyut di sawah, tambak, dan pasar desa.
Sejak Januari 2025, MBG hadir bukan sekadar intervensi gizi, tetapi injeksi fiskal terbesar dalam sejarah otonomi daerah. RAPBN 2026 mengalokasikan sekitar Rp335 triliun untuk 82,9 juta penerima di 514 kabupaten/kota—mendekati 8,8 persen dari total belanja negara Rp3.786 triliun. Angka yang membuat kepala daerah tergoda sekaligus waswas: bagaimana memastikan uang sebanyak itu tidak hilang di jalan, tapi memutar ekonomi lokal dan menyelamatkan fiskal daerah yang kian terhimpit?
Hitungannya terang-benderang. 82,9 juta penerima × 200 hari × Rp20 ribu per porsi = Rp335 triliun setahun. Bila 70–80 persen diserap produk lokal—beras, sayur, ikan, susu—maka Rp234–268 triliun akan berputar di desa dan kota. Dengan multiplier konservatif 1,2–1,4, dampaknya bisa menambah ±0,5 poin pertumbuhan PDB, menurunkan kemiskinan, dan mempercepat penurunan stunting.
Dengan 41.450 dapur layanan berkapasitas 2.000–3.000 porsi per hari, serapan kerja bisa mencapai 829 ribu orang (20 pekerja per dapur). Bila dua shift diberlakukan, tenaga kerja bisa menembus ±1,7 juta. Sebuah mesin gizi sekaligus mesin ekonomi terbesar dalam sejarah daerah.
Tapi semua potensi itu akan sia-sia bila kepala daerah hanya sibuk mengeluh soal transfer menyusut dan kewenangan ditarik pusat. Rakyat tidak makan keluhan. Mereka butuh kepemimpinan yang menghadirkan hasil nyata: piring makan anak-anak terisi, pasar rakyat bergairah, nelayan dan petani tersenyum karena pendapatan naik.
Bone Bolango hanya contoh kecil. Di pesisir Bone, nelayan berharap kontrak ikan untuk dapur MBG. Di Tapa, petani sayur ingin ada kepastian harga. Di Kabila, petani padi bermimpi gabah mereka dibeli untuk nasi anak-anak sekolah. Bayangkan bila semua kabupaten melakukan hal serupa. Bukankah ini jalan selamat bagi kepala daerah di era fiskal ketat?
Tentu pusat harus menata arsitektur nasional. Bentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berstandar nasional. Siapkan e-Katalog lokal agar UMKM bisa ikut tanpa birokrasi berbelit. Bayar dengan sistem T+7 agar usaha kecil tidak megap-megap arus kas. Bangun dashboard real-time dan open contracting agar tak ada celah rente. Pusat justru untung: dengan tata kelola digital, program ini akan jadi warisan politik yang harum.
Daerah pun harus gesit. Dirikan aggregator pangan berbasis koperasi atau BUMDes. Tetapkan Local Sourcing sampai 80 persen, tentu selaras aturan LKPP dan persaingan sehat. Latih UMKM katering sehat. Dorong urban farming di pekarangan dan lahan tidur. Pastikan setiap rupiah MBG berputar dulu di ekonomi setempat sebelum mengalir ke luar.
Kepala daerah bisa memulai dengan agenda 90 hari pertama yang konkret: kontrak panen dan tebar dengan petani-peternak lokal; dapur modular berkapasitas 2.000–3.000 porsi per hari dengan menu bergizi dan higienitas ketat; pembayaran cepat T+7 lewat Bank Daerah atau Himbara; dashboard publik berisi harga, vendor, uji gizi, jumlah porsi, dan whistleblowing system; pelatihan QA pangan, manajemen, cold chain, sertifikasi halal; serta monitoring bulanan dampak serapan lokal, tenaga kerja, omzet UMKM, tambahan PAD. Semua diumumkan rutin agar rakyat melihat manfaatnya, bukan hanya mendengar pidato.
Risiko klasik tetap mengintai: rente, mark-up, vendor tunggal. Ini hanya bisa dicegah dengan larangan konsentrasi pasar, kontrak berjenjang berbasis kinerja, audit operasional paralel, dan keterlibatan masyarakat sipil memantau jalannya program. Integritas bukan jargon, ia syarat mutlak agar setiap rupiah kembali ke sawah, tambak, dan bengkel UMKM.
Bagi pusat, mendukung desain ini justru membawa keuntungan strategis. Dengan tata kelola digital dan transparansi penuh, pemerintah pusat akan tercatat dalam sejarah sebagai inisiator warisan fiskal terbesar yang langsung menyentuh rakyat kecil. Angka stunting turun, PDRB daerah naik, dan publik melihat pusat-daerah kompak, transparan, dan berorientasi hasil.
Sejarah tidak menulis nama pengeluh. Ia menulis nama mereka yang bekerja melampaui keterbatasan. MBG adalah peluang emas untuk membalik cerita otonomi: dari keluhan fiskal sempit menjadi lompatan kesejahteraan nyata.
Bone Bolango sudah menunggu. Nelayan di pesisir Bone, petani sayur di Tapa, petani padi di Kabila—semua berharap program ini tak berhenti di meja birokrasi. Kepala daerah di seluruh negeri semestinya menangkap harapan itu. Bekerjalah dengan akal, hati, dan tata kelola modern. Biarkan data—bukan retorika—yang bicara: stunting turun, PDRB daerah naik, dompet keluarga menebal. Itulah ukuran kepemimpinan di era fiskal ketat.
*) Mantan kepala daerah, pengamat kebijakan dan inovasi daerah, Inisiator Nusa Strategika