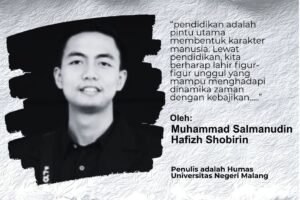Oleh: Dahlan Iskan
SEMUANYA persis sesuai dengan skenario. Sampai ke tanggal-tanggalnya. Termasuk tanggal dilakukannya pergantian anggota kabinet periode kedua Presiden Jokowi kemarin.
Babak pertamanya: Airlangga mundur dari jabatan ketua umum Partai Golkar. Sudah dilakukan. Tepat waktu. Guyonnya, saat duduk di mana pun kini Airlangga enggan berdiri –khawatir kursinya diambil orang. Babak kedua: Rapim Golkar. Juga sudah terjadi. Juga sesuai dengan skenario –tanggalnya dan personalianya.
Jadwal berikutnya pergantian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly. Harus sebelum tanggal 20 Agustus –harus sebelum Munaslub Golkar. Sudah terjadi kemarin. Yasonna yang PDI-Perjuangan diganti Supratman Andi Agtas dari partai Gerindra.
Anda pun sudah tahu babak selanjutnya: siapa yang bakal jadi ketua umum Partai Golkar. Pastilah Bahlil Lahadalia. Yang kemarin mendapat jabatan baru sebagai menteri energi dan sumber daya mineral.
Meski dari profesional, Arifin Tasrif –yang diganti Bahlil– diidentifikasi sebagai orangnya ketua umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Yang bukan analis politik pun tahu: hasil Munaslub Golkar harus dimintakan pengesahan pemerintah. SK pengesahan dari menkum HAM. Harus cepat. Sudah harus ditandatangani sebelum 25 Agustus. Maksudnya, agar ketua umum yang baru bisa menandatangani surat rekomendasi pencalonan para kepala daerah sebelum jadwal pendaftaran di KPU tanggal 27 Agustus.
Semua sudah diatur rapi. Yang kira-kira jadi faktor penghambat harus disingkirkan lebih dulu. Tidak boleh ada ewuh pakewuh. Tidak boleh ada rasa sungkan. Tujuan harus tercapai. Yang tidak mau mendukung tidak boleh menghambat.
Yasonna belum terbukti menghambat. Atau akan menghambat. Tapi bukti tidak penting. Di pengadilan pun bukti juga kalah oleh lembaran Benjamin Franklin. Apalagi ini bukan proses peradilan. Ini proses politik.
Maka siapa saja hanya bisa geleng-geleng kepala –itu pun bagi yang masih punya leher.
Agar tidak terus geleng-geleng kepala sampai bulan November, baiknya jangan punya kepala –terutama isinya.
Harus diterima apa adanya: presiden punya hak prerogatif. Pun di masa injury time. Periodisasi kepresidenan tidak mengenal istilah injury time.
Apakah semua yang terjadi itu kejam? Tidak.
Apakah semua yang terjadi itu bisa dibenarkan? Bisa.
Apakah semua yang terjadi itu legal? Sangat legal.
Apakah ada peristiwa politik yang lebih dahsyat dari yang sekarang ini? Ada.
Jadi untuk apa terus-menerus geleng-geleng kepala.
Anda masih ingat jargon “Akselerasi Pembangunan 25 tahun”?
Itu adalah ”buku induk” untuk mengawali Orde Baru. Itu adalah tahapan pembangunan jangka panjang yang terencana. Agar negara bisa tinggal landas menuju kemajuan.
Setelah ”akselerasi” itu ada Trilogi Pembangunan: stabilitas, pertumbuhan, pemerataan. Keamanan harus stabil. Politik harus stabil. Pertentangan politik kanan-kiri harus dibasmi. Partai-partai kanan disatukan dalam PPP. Partai-partai sekuler dilebur dalam PDI. Diciptakanlah partai tengah yang dominan yang tidak disebut partai: Golkar.
Penentangan luar biasa. Tapi yang menentang ditendang. Komando Jihad diciptakan sebagai jebakan untuk memberangus ekstremis dalam Islam.
Partai nasionalis, Partai Kristen dan Katolik disatukan dengan konsensus: ketua umumnya harus Banteng, sekjennya harus dari partai Kristen.
Kata ”konsensus” menjadi mantra saat itu –mirip mantra demokrasi saat ini. Mantra ”konsensus” dipuja sebagai tandingan atas konsep demokrasi –yang distigmakan secara negatif dengan istilah demokrasi liberal.
Semua keputusan diambil berdasar konsensus. Bukan dengan pemungutan suara. Hasil pemilu bisa diketahui dengan cepat –Golkar pasti menjadi pemenangnya.
Apa yang terjadi sekarang sama sekali tidak sekejam yang terjadi pasca ditetapkannya ”Akselerasi Pembangunan 25 tahun”.
Bagi yang merasa drama politik sekarang ini kejam, ketahuan: Anda tidak pernah menikmati lezatnya KKN di masa Orde Baru. (***)