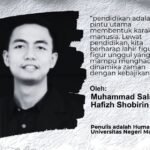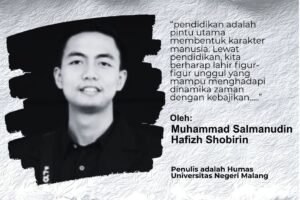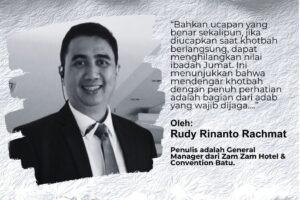Oleh: Matthoriq
Mahasiswa Doktoral Ilmu Administrasi UB PB LPDP PK-225 Jagat Nirmala
Dalam suatu diskusi sesi kelas luring, dosen pengampu ekonomi politik kebijakan publik membawa dalam keheningan sejenak saat mengemuka suatu pernyataan “penguasa dan pengusaha”. Tampaknya memang acapkali terdengar dalam ruang temu dan wicara baik formal maupun embongan (red:akar rumput) antara circle entitas penguasa dan pengusaha dalam berbagai laku demokrasi masyarakat Indonesia.
Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan, telah dianut Negara Indonesia sejak awal berdiri. Corak demokrasipun di Indonesia mengalami beberapa perubahan mulai demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin (masa orde lama kepemimpinan Presiden Soekarno); kemudian digaungkan demokrasi pancasila (masa orde baru kepemimpinan Presiden Soeharto); dan setelah reformasi tahun 1998 menjadi demokrasi liberal di mana adanya titik berat pada kebebasan individu terutama perihal hak-haknya sebagai manusia, individu dan warga negara. Sehingga salah satu ukuran kesuksesan demokrasi adalah penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).
Interaksi penguasa dan pengusaha memang selalu menarik belakangan ini pasca reformasi. Terlebih menggeliat bahkan jamak pada kontestasi demokrasi prosedural (elektoral).
Sebuah literatur An Introduction to Political Economy yang ditulis Robert Page Arnot bahwa kebijakan publik dalam political economy perspective dapat disimbolisasi orkestrasi pendulum antara political power dan economic interest.
Setidaknya kurang lebih dua dekade sejak pertama kalinya Pilkada dihelat pada Juni 2005 di Kabupaten Kutai Kertanegara, banyak pengusaha yang terjun bahkan berambisi menjadi aktor penting penentu keputusan politik (public policy).
Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK bahkan pernah menyebut secara gamblang nama Jusuf Kalla, Suryo Paloh, Sandiaga Uno, Hary Tanoesoedibjo, atau Airlangga Hartarto adalah para businessman yang memiliki karier mulus dalam melakoni banting setir menjadi politisi, karena memang beragam latar profesi cenderung meminati (tergiur) berada pada arena percaturan tampuk kekuasaan (political power).
Barangkali tepat jika pernah mengemuka sebutan “penguasaha” dengan meminjam terminologi dwifungsi ABRI, yang untuk memberikan pengistilahan dwifungsi pengusaha yang sekaligus penguasa.
Walaupun demikian dalam disiplin perkembangan ilmu administrasi publik dikenal Reinventing government (red: Mewirausahakan Birokrasi) yang diperkenalkan D.Osborne dan T. Gaebler (1993) yang diyakini sebagai oase dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Hingga kemudian karya cukup fenomenal dari seorang Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad kala itu dalam bukunya “Reinventing Local Government: Pengalaman dari Daerah” (2008) dan kemudian pada tahun 2018 dikukuhkan menjadi Guru Besar Kewirausahaan Sektor Publik Pertama di Indonesia dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, dengan orasi ilmiah yang berjudul “Peran Kewirausahaan Sektor Publik Model Fadel untuk Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah”.
Fadel Muhammad yang notabene sebelum memasuki dunia politik lebih dikenal sebagai entrepreneur, pebisnis dengan jabatan strategis berbagai sektor dan perusahaan.
Kembali pada uraian sang dosen yang berlatar doctor rerum politicarum dari University of Potsdam, Germany yang melemparkan pemantik bahwa adanya kecondongan pemerintah saat ini dalam memperkuatkan institusi (sektor) ekonomi namun institusi maupun kehidupan demokrasi mesti perlu koreksi.
Meskipun adanya aktualisasi Public Private Partnership melalui skema formal Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (dulu Kerjasama Pemerintah dan Swasta) dan kini juga dilengkapi dengan mekanisme Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA). Diakui berbagai pihak, pemerintah saat ini terbukti serius membangun infrastruktur dalam konteks ini ekonomi.
Hal ini bukan berarti tidak perlu penguatan pula pada aspek institusi dan kehidupan berdemokrasi. Karena merujuk uraian sebelumnya, bahwa demokrasi memberi pemaknaan akan kebebasan individu terutama perihal hak-haknya sebagai manusia, individu dan warga negara. Walaupun semua tahu, manakala ketersedian infrastruktur dikelola optimal diharapkan mampu memberi manfaat (dampak) baik segi ekonomi, sosial dan budaya.
Setidaknya, mengutip Kompas.id (2024) bahwa Indeks Demokrasi Indonesia dari Freedom in The Worlds (Freedom House) menurun stag sejak 10 tahun terakhir; Democracy Index (IUE) berada pada skor merah; sedang dalam IDI (BPS) adanya peningkatan dari Sedang selama 10 tahun menjadi Baik pada 2022 dengan angka 80,41. Sementara capaian Corruption Perception Index (CPI) tahun 2023 dan 2022 yang masih stag di angka 34/100 berperingkat 115 dari 180 negera yang disurvei.
Berkaitan Hak dalam pembangunan, Pariwisata merupakan sektor pembangunan potensial sekaligus berdaya ungkit strategis baik di level daerah dan nasional bahkan dunia internasional. Pendapatan devisa sebelum dampak pandemi Covid-19 pada rentang 2013-2019 yakni USD10,1 miliar (2013) menjadi USD17,76 miliar (2019); sedangkan di tahun 2022 terjadi lonjakan yang melejit dari USD0,49 miliar (2021) menjadi USD4,26 miliar pada 2022 (Data Indonesia, 2022).
Terbaru, Kemenparekraf merilis angka fantastis bahwa dampak libur lebaran 2024 kemarin, memperkirakan Rp369,8 triliun sebagai nilai perputaran ekonomi sektor parekraf yang dihitung dari pengeluaran biaya berdasarkan durasi wisata (Kemenparekraf, 2024).
Hal lain yang tak kalah menarik dengan adanya penetapan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dengan nilai anggaran sebesar Rp9,35 triliun di mana juga tetap membuka selebar-lebarnya investasi private sector guna mendukung sarana prasarana Destinasi khususnya Konektivitas, Sumber Daya Air, Permukiman, dan Perumahan. Lima destinasi yang berada pada lima provinsi yaitu Danau Toba (Sumut); Borobudur (Jateng); Labuan Bajo (NTT); Mandalika (NTB); dan Likupang (Sulut).
Berbicara lima DPSP tersebut juga sempat mencuat viral manakala Myra P. Gunawan seorang dosen senior ITB yang juga bagian dari perintis lembaga penelitian mengenai kepariwisataan tertua di Indonesia yang didirikan pada tahun 1993, memberikan sebuah kritik atas perkembangan “(kebocoran)” pariwisata dewasa ini.
Namun perlu kita ingat, bahwa proyek mercusuar tersebut berada pada daerah, sehingga dalam konteks otonomi daerah (UU 23/2014: 108) harusnya terjadi kolaborasi dan sinergitas pengelolaan atas pembagian urusan pemerintahan secara konkuren antara destinasi pariwisata nasional, destinasi pariwisata provinsi, destinasi pariwisata kabupaten/kota.
Rencana dan target pembangunan pariwisata yang terkesan ambisius harus tetap sering merefleksi bahwa belum sepenuhnya baseline kinerja sektor “pemersatu” tersebut berkinerja baik. Harus diakui masih terbatasnya 3 A pariwisata (Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas) dan kecenderungan masih rendahnya pengelolaan dan penerapan parwisata berkelanjutan menjadi determinan kausal sebabnya.
Jumlah kunjungan wisata yang belum optimal, pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata belum sepenuhnya berjalan; kontribusi terhadap PDRB belum meningkat signifikan, keberpihakan pelaksanaan pariwisata yang melibatkan secara optimal masyarakat lokal, kunjungan masih belum sepenuhnya beriorientasi pada wisata berkelanjutan yang identik pada wisata alam dan budaya adalah sebagian potret di daerah.
Penyelenggaraan pengelolaan potensi sumberdaya pariwisata yang hanya berbasis pada pendekatan industri semata akan menjadi kondisi kontraproduktif manakala kehilangan spirit keberlanjutan. Gagasan pendekatan pengembangan wisata premium (melalui sebutan Destinasi Super Prioritas) tidak boleh melupakan Hak Prioritas.
Berkaitan Hak, bila merujuk amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun tentang Kepariwisataan bahwa adanya kebebasan dan memanfaatkan waktu luang dalam bentuk berwisata merupakan dari hak asasi manusia. Berwisata seharusnya diposisikan sebagai kebutuhan sehingga mendapatkan atensi khusus sebagai bagian penting dari HAM (UC, 2022).
Selain itu termaktub pula dalam UU Kepariwisataan bahwa juga terdapat pengaturan Hak Prioritas, yang ditujukan kepada di mana masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata untuk terlibat dalam pengelolaan. Artinya sudah sejauh mana ruang kolaborasi pengelolaan destinasi pariwisata dan sudah berapa banyak wisata rakyat secara inklusif dalam upaya pemenuhan hak berwisata bagi warganya sehingga berwisata menjadi mudah, dekat dan murah.
Padahal pada era paradigma governance di mana perlunya pelibatan interaksi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, organisasi nonpemerintah dan sektor lainnya untuk mencapai hasil yang diinginkan sehingga tercipta ruang proporsional partisipatif antar pihak melalui pemerintahan kolaboratif (Prasojo,2021; Wijaya,2023; Saleh,2024).
Beriring Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII Tahun 2024, yang jatuh pada puncaknya 25 April, yang juga masih dalam suasana Idul Fitri kiranya menjadi tepat ungkapan bahwa Super Prioritas pada destinasi pariwisata itu “halal” merujuk tujuannya, dan Hak Prioritas sebagai hak masyarakat itu “halal”, sehingga dalam menguatkan sistem dan pelaksanaan otonomi daerah kepariwisataan perlu terus didorong agar tercipta governansi pemerintahan yang lebih demokratis yang ditopang stabilitas ekonomi dan politik. (***)
Sunan Muria, 24 April 2024
Penulis