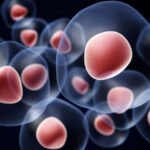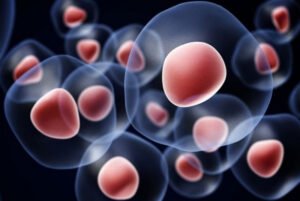SAYA merasa ikut bersalah. Saya pernah mengangkat orang seperti Emirsyah Satar menjadi dirut Garuda Indonesia.
Yang belakangan ternyata terbukti melakukan korupsi. Lewat cara yang tidak mungkin saya ketahui. Juga tidak bisa diketahui oleh pengusaha besar yang begitu ”keras” dalam menyikapi keuangan: Chairul Tanjung.
Padahal CT itu –begitu boss CTCorp itu biasa dipanggil– adalah pemegang saham yang cukup besar di Garuda: hampir 29 persen.
Saya pernah berbicara dengan CT. Bertiga. Topiknya: bagaimana orang seperti ia dan saya bisa tertipu melihat Emirsyah Satar. Yang secara perusahaan, di bawah Satar, Garuda memang terlihat maju sekali. Kami begitu marah saat itu. Merasa dikhianati.
Korupsinya begitu canggih. Tidak ada lembaga pengawas di Indonesia yang bisa mengetahui. Tidak pula Dewan Komisaris Garuda. Korupsi Satar itu hanya bisa terbongkar justru karena ada peristiwa korupsi yang terungkap di luar negeri. Ternyata Satar mengambil komisi dari pengadaan pesawat Garuda.
Saya dan CT lama terdiam berdua. Kok bisa dikecoh oleh Satar. CT lebih marah lagi. Ia merasa pengorbanannya menolong keuangan Garuda seperti dicampakkan. Akibat menolong Garuda itu, CT sekarang dirugikan sekitar Rp 4 triliun.
Di swasta, untuk pengadaan barang yang begitu besar, bukan direksi yang melakukan. Melainkan pemilik perusahaan.
Karena itu tidak perlu ada komisi. Komisi seperti itu harus dimasukkan dalam potongan harga barang. Dengan demikian perusahaan mendapat pesawat lebih murah.
Di swasta, kalau pun yang melakukan pembelian adalah direksi itu hanya tahap negosiasi. Kata akhir tetap ada pada pemilik perusahaan –pemegang saham.
Di swasta, yang biasa terjadi adalah begini: direksi sudah melakukan negosiasi untuk membeli sesuatu. Sudah ditawar habis. Harga sudah disepakati. Tapi untuk pembayaran harus melibatkan pemegang saham.
Di tahap itulah pemegang saham bertemu pihak penjual. Ia mengatakan tanpa basa basi: saya bisa menyetujui keputusan direksi saya, kalau harga itu dipotong sekian persen.
Artinya, negosiasi final ada di pemegang saham. Pemegang saham seperti CT, atau saya, biasa melakukan itu. Di swasta. Orang seperti kami biasa curiga. Jangan-jangan ada komisi di balik transaksi itu. Maka kemungkinan adanya komisi itulah yang kami ambil –untuk penghematan di perusahaan. Perusahaan bisa mendapat barang lebih murah.
Lama-lama direksi kami tahu: tidak ada gunanya berusaha cari komisi. Lama-lama membudayalah menjadi perusahaan yang lebih bersih.
Prinsip seperti itulah yang sulit dilakukan di BUMN. Apalagi BUMN yang sudah go public seperti Garuda. Pemegang saham tidak boleh mencampuri urusan direksi. Sama sekali. Begitu pemegang saham campur tangan akan dianggap melanggar UU.
Apalagi di BUMN itu begitu sering ganti direksi. Juga harus ganti pemegang saham tiap lima tahun –sesuai dengan jadwal Pemilu lima tahunan. Membudayakan perusahaan bersih sulit sekali dilakukan. Sebelum budaya bersih terbentuk sudah berubah lagi. Beda dengan di swasta. Yang pemegang sahamnya itu-itu terus. Yang direksinya itu-itu terus. Budaya apa saja bisa dibentuk dengan utuh di swasta. Yang jelek maupun yang baik.
Di BUMN juga sudah membudaya mengatur buku keuangan. Sebagian untuk menutupi kelemahan direksi yang sedang menjabat –karena ingin agar bisa terus menjabat. Sebagian untuk menutupi kelemahan direksi sebelumnya.
Kelemahan buku keuangan sebelumnya ditutupi dengan penukangan buku keuangan yang baru. Kalau tidak melakukan itu maka buku direksi yang baru tidak akan kunjung baik. Rapornya akan jelek.
Apalagi kalau direksi baru itu bukan saja tidak mampu menutupi lubang lama. Tapi justru hanya bisa membuat lubang baru. Yang lebih dalam.
Maka pekerjaan setiap direksi hanya menutup lubang lama. Sambil membuat lubang baru yang lebih dalam.
Tidak semua BUMN begitu. Banyak yang tidak begitu.
Menjadi menteri lima tahun –apalagi hanya tiga tahun seperti saya– apa yang bisa dilakukan?
Kuncinya tinggal satu: memilih orang yang benar. Dengan risiko, ketika memilih 10 orang benar ternyata yang benar-benar baik hanya 8 orang. Ada saja orang hebat seperti Satar. Saya menyesal tidak mendengarkan bisikan istri saya: hati-hati dengan orang itu. Padahal dia membisikkannya tidak hanya satu kali. Kadang-kadang bisikan istri harus didengar –istri punya indra yang berbeda.
Persoalan menutup lubang lama, lalu membuat lubang baru yang lebih dalam itu, kini menjadi lebih dramatis: ketika terjadi pandemi Covid-19. Ketika pendapatan Garuda menurun –anjlok– tinggal 10 persen. Siapa pun pusing menghadapi persoalan Garuda sekarang ini.
Saya pun tidak punya kemampuan usul apa-apa –kecuali ini: direksi Garuda tidak perlu malu ke PKPU. Garuda akan lebih sehat nanti. Operasional Garuda akan lancar kembali.
Kalau malu datang ke PKPU mintalah komisaris untuk mendampingi. Orang seperti Yenny Wahid akan mau. Toh selama jadi komisaris, Mbak Yenny hanya lebih banyak dapat bully daripada dapat gaji. Begitu diangkat jadi komisaris hanya terima 50 persen gaji. Lalu, ketika Garuda kian sulit, dia minta tidak usah digaji.
Jangan minta uang ke pemerintah. Jangan. Pemerintah sudah sangat sulit.
Tanggalkan gengsi dan malu. Pergilah ke PKPU. Jangan tunggu pemberi utang yang ke PKPU. Mereka tidak akan mau ke PKPU.
Pakailah masker rangkap lima ketika datang ke PKPU –untuk mengurangi rasa malu dan gengsi yang tinggi. Gengsi tidak akan bisa menyelamatkan siapa-siapa.
Dulu, tidak pernah cukup alasan membawa Garuda ke PKPU. Tidak pernah terjadi, pendapatan merosot sampai 90 persen seperti sekarang. Mumpung ada pandemi. Siapa pun bisa menerima alasan itu. (*)