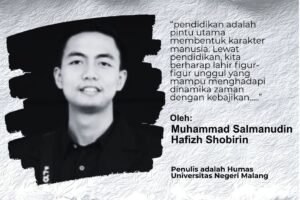Saat ini sebagai konsekuensi revolusi teknologi informasi demokrasi telah mengarah pada arena digital (Demokrasi digital). Awalnya efeknya positif karena memperbesar arena partisipasi politik dari sebelumnya dominan di ruang offline ke ranah online. Hadirnya banyak platform media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram dan Youtube semakin mempermudah masyarakat untuk mengartikulasikan pandangan dan tindakan politiknya. Demokrasi ala daring seperti ini memfasilitasi ruang bagi masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan kebijakan beserta kontrolnya. Demokrasi digital menjadi arena ruang publik virtual yang dapat memfasilitasi perbincangan mengenai isu-isu politik yang lebih interaktif, egaliter dan tidak terbatas.
Di Indonesia, twiter menjadi salah satu media sosial arus utama yang memfasilitasi eksistensi demokrasi digital. Kelebihanya berupa kepraktisan dalam berkomunikasi, digemari oleh banyak masyarakat Indonesia khususnya generasi milenial dan Z. Maka tidak salah jika Indonesia ada di peringkat kelima sebagai pengguna terbanyak Twitter di Dunia.
Twiter memang menawarkan kemudahan akses bagi siapa saja. Namun disitulah masalah yang terjadi selanjutnya. Ada lubang hitam yang mengintai berupa aktifitas perundungan (cyber bullying). Twitter menjadi arena pergunjingan politik yang penuh dengan caci maki, pembunuhan karakter (doxing) dan berkontribusi pada penyebarluasan hoax tanpa terkendali.
Awalnya, twitter yang diharapkan mencipatakan ruang bagi terbentuknya deliberasi politik justru disaat bersamaan menimbulkan kebisingan politik (noise) melalui serangkaian tindakan dehumanisasi. Salah satu bentuk ekstremnya adalah digital mobokrasi, sebuah kondisi dimana terjadi upaya kolektif dari gerombolan pengguna twiter untuk menyerang seseorang. Model ini begitu menakutkan sebab seringkali bekerja sangat reaktif dan diorganisir secara sistematis untuk membunuh karakter seseorang yang salah satunya melalui teknik asosiasi (pelabelan buruk) dengan informasi sesat.
Disinilah buzzer berperan. Istilah buzzer memang belakangan ini teraksentuasi negatif karena dianggap menjadi sumber keresahan dan konflik horizontal di twiter. 2 tokoh publik terbaru yang merasakan keganasan serangan para buzzer adalah Kwik Kian Gie dan Susi Pujiastuti. Keduanya dibombardir secara bergelombang oleh para buzzer atas sikap kritis terhadap pemerintah dan anasirnya.
Yang begitu membahayakan dari dengungan para buzzer karena mengarah pada upaya menguliti masalah pribadi (doxing) dan beberapa tuduhan tidak berdasar. Privasi orang diumbar didepan publik agar reputasi mereka jatuh sehingga kritiknya tidak perlu didengar. “aib” tersebut sengaja disebarluaskan untuk menempelkan kesan buruk pada seseorang sehingga opininya sangat perlu dikesampingkan karena statusnya sebagai orang yang bermasalah.
Begitulah kelihaian buzzer dalam membangun opini dan meramaikanya. Istilah buzzer yang diawal kemunculanya berkonotasi positif karena menjadi strategi marketing produk barang dan jasa seketika berubah buruk ketika terjun dalam dunia politik. Perubahan kesan tersebut terjadi karena sejak kemunculanya pada Pilkada 2012 buzzer bertransformasi sebagai salah satu aktor politik partisan yang sangat sering terlibat dalam kampanye dan propaganda politik hitam. Kecerdasan mereka dalam mengamplifikasi isu seringkali digunakan untuk memanipulasi opini publik dengan fitnah dan pembunuhan karakter. Upaya desktruktif tersebut ditunjang dengan jejaring mereka yang sangat luas di twitter sehingga informasi yang disebarkan menjadi pusat perhatian. Itu semakin jadi soal karena karakterisik netizen (publik) kita yang literasi digitalnya rendah di era post truth ini.
Buzzer itu profesi yang menggiurkan karena didasari oleh dorongan ideologis dan ekonomis bahkan kedua-duanya. Mengikuti logika pasar dimana industri hadir karena ada permintaan, buzzer terus eksis karena politisi butuh mereka. Kemampuan melakukan kampanye politik secara efektif dan efisien menjadikan buzzer sangat laku dalam politik Indonesia. Ini dikonfirmasi oleh dua temuan, Pertama, dari lembaga riset Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) di tahun 2017 yang memberi bukti bahwa sejak Pilkada DKI Jakarta 2012 eksistensi buzzer terus berlanjut pada Pilpres 2014 dan Pilkada DKI Jakarta 2017. Temuan serupa juga berasal dari riset Bradshaw & Howard (2019) yang dengan tegas menyebut bahwa politikus dan partai politik Indonesia membayar pasukan siber atau buzzer untuk memanipulasi opini publik demi kepentingan elektoral.
Jalan Keluar
Menertibkan buzzer pelanggar hukum dan norma sosial memang sangat sulit. Banyak diantara mereka yang menggunakan akun anonim (tanpa identitas) bahkan menggunakan akun bot sehingga sulit terdeteksi. Belum lagi jika ada kekuatan besar yang sengaja melindungi mereka. Namun apapun kondisinya, pemerintah perlu tegas. Ini menjadi titik krusial mengingat selama ini buzzer terus ada karena lemahnya fungsi penindakan pemerintah. Ini juga diperkuat oleh premis bahwa buzzer yang satu faksi dengan pemerintah terkesan dilindungi.
Ada beberapa Langkah startegis secara kolektif yang dapat dilakukan. Pertama, pemerintah lebih memaksimalkan patroli siber di media sosial khususnya twitter. Pertumbuhan mereka yang sangat cepat perlu diimbangi oleh kesigapan pemerintah untuk langsung mematikan akun buzzer yang bermasalah dan melanjutkanya ke penindakan hukum. Tentu itu pekerjaan yang tidak sulit sebab pemerintah lewat kepolisian dan Kementrian Teknologi dan Informasi (Kominfo) punya alat yang canggih. Tinggal dikuatkan dengan Konsistensi, ketegasan dan keadilan. Khusus kata terakhir penting untuk mengembalikan kepercayaan publik yang selama ini melihat kesan tebang pilih karena banyak buzzer pendukung pemerintah dan anasirnya yang tidak ditindak.
Kedua, mustahil juga menjadi tanggungjawab semata pemerintah, netizen (publik) disaat bersamaan juga wajib meningkatkan literasi informasi digitalnya. Tujuanya menangkal informasi-informasi menyesatkan sehingga dengan sendirinya pengarusutamaan isu lewat manipulasi opini yang diorganisir oleh para buzzer tidak bekerja karena minimnya respon oleh netizen.

Penulis : Iradhad Taqwa Sihidi (Dosen Ilmu Pemerintahan UMM Malang)