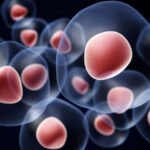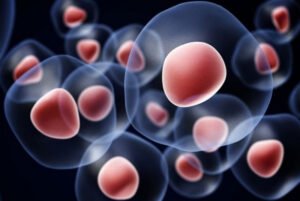Oleh: Dahlan Iskan
DISWAY hari ini saya tulis di rumah sakit: saya terkena Covid-19.
Awalnya saya tidak mau masuk RS. Terlalu banyak yang bercerita di RS justru berbahaya. Toh tidak ada keluhan yang berat. Hanya batuk-batuk kecil. Tidak demam. Sambal istri saya masih terasa pedasnya. Masih menitikkan air liur.
Tapi dua anak saya memaksa. Kebetulan ada satu kamar baru kosong di RS langganan keluarga. Setidaknya mumpung ada kamar.
Batuk-batuk kecil itu terjadi sehari sebelumnya: Sabtu. Pagi itu saya masih olahraga satu jam di halaman depan Graha Pena. Lalu sarapan. Setelah itu perut saya kembung. Batuk-batuk kecil. Saya pikir akibat sambal tomat hijau yang terlalu banyak.
Lalu saya minum 4 kapsul Lian Hua. Siangnya 4 kapsul lagi. Sore lagi. Kembung perut berkurang. Saya pun pup lima kali. Tapi tidak diare.
Minggu pagi besoknya kondisi lebih baik lagi. Saya mau berangkat olahraga. Anak saya melarang. Lalu: saya, istri, dan Kang Sahidin test antigen: saya positif. Istri dan Kang Sahidin negatif.
Setelah tahu positif: masuk RS atau tidak? Atau swab PCR dulu?
Saya ikuti keinginan anak-anak: masuk RS. Tapi tidak boleh langsung ngamar. Ditangani dulu di UGD: Swab-PCR.

Sambil menunggu hasil lima jam menunggu dilakukan banyak hal: ukur tekanan darah (144/77), level oksigen (97), suhu badan (38, tinggi), detak jantung (71), pemeriksaan jantung (bagus), CT Scan paru-paru (bersih). Di UGD itu saya langsung diinfus penurun panas. Setengah jam selesai.
Jam 23.00 hasil PCR keluar: positif. Strong positif.
Ternyata hasil PCR itu empat macam: negatif, weak positif, positif, dan strong positif. Berarti positif saya ini tidak main-main.
Saya langsung ngamar.
Perasaan saya biasa saja. Toh saya tahu jantung dan paru-paru saya baik.
Betul juga saya mengikuti keinginan anak-anak. Kalau isolasi di rumah, saya tidak akan tahu kondisi organ-organ tersebut. Jatuhnya hanya menduga-duga. Yang justru bisa bikin was-was.
Saya sudah membawa koper yang disiapkan istri: pakaian dan peralatan mandi. Juga obat-obatan wajib, terkait transplant hati dulu termasuk obat penurun imunitas.
Saya langsung tidur. Nyenyak. Sambil diinfus vitamin. Jam 04.00 saya terbangun. Mau kencing. Saya lihat botol infusnya kosong. Saya hubungi perawat. Diganti infus baru dengan isi yang sama.
Saya tidur lagi.
Pagi-pagi suster masuk ruangan. Rutin. Test tekanan darah, oksigen, suhu, dan seterusnya. Hasilnya sama bagus dengan sebelumnya. Bahkan suhu badan saya sudah 36,6. Suster lalu mencopot infus yang sudah kosong.
Tidak ada infusan baru.
Lapar.
Tidak ada pisang. Tidak ada jus jambu merah. Tidak ada dua telur rebus-lunak. Tidak ada pecel. Tidak ada brokoli rebus. Tidak ada sayur. Tidak ada madu.
Eh, madu ada. Saya bawa dari rumah.
Saya rebus air. Untuk minum madu. Tidak kenyang tapi lumayan. Sambil menunggu jatah sarapan dari rumah sakit.
Siang harinya perawat melakukan tes lagi. Hasilnya masih tetap baik. Suhu 36,6; tekanan darah 137/69; detak jantung 71; oksigen 96.
Dokter penyakit dalam minta bicara lewat video: Dokter Purnomo Budi Setiawan. Saya kenal lama. Ia dokter yang menangani sakit lever saya, sejak sebelum transplant. Sekarang sudah profesor.
“Fungsi levernya baik sekali,” ujar beliau. “Obat-obat terkait transplant terus saja diminum,” tambahnya.
Meski video call, saya tidak bisa melihat wajah beliau. Rapat tertutup oleh APD kelas berat. Mungkin beliau juga lagi di rumah sakit. Saya kangen sebenarnya. Sudah lama tidak bertemu. Tapi ya sudah, ada Covid.
Tak lama kemudian ketua tim dokter masuk kamar. Tapi saya lagi video call dengan Singapura dan Tiongkok. Beliau keluar lagi ke kamar lain.
Setelah itu saya tidak mau terima telepon. Agar ketika beliau kembali saya sudah siap.
Saya pun diperiksa di bagian dada dan punggung. Dengan stetoskop. Saya disuruh tarik napas dan melepaskannya. Di 8 titik dada dan 8 titik punggung. Saya tahu itu untuk mendeteksi paru-paru. Yakni organ paling menarik perhatian di pasien Covid-19.
Namanya: dr Hanny Handoko. Laki-laki. Ahli paru dari Unair, Surabaya. Yang pernah memperdalam ilmunya di National University of Singapura.
Saya nanti akan bertanya tentang stetoskop yang ia gunakan. Kok berbeda dengan stetoskop biasanya yang kita kenal.
Tapi beliau duluan bercerita. “Kita pernah bertemu di Malang,” katanya. Lama sekali. Mungkin 20 tahun lalu.
Waktu itu dokter Hanny menjadi pejabat di bawah wali kota Malang, yang juga dalang itu. Sebelum akhirnya berlabuh di RSAL Surabaya. Dan sekarang di RS swasta ini.
Umurnya 59 tahun. Anaknya dua. Yang pertama S1 di Melbourne. Kini di fakultas kedokteran di Queensland. “Di sana untuk masuk FK harus S-1 dulu,” ujar dr Hanny. S-1nya 3 tahun. Pendidikan dokternya 4 tahun. Total 7 tahun. Sebenarnya kurang lebih sama dengan waktu pendidikan dokter di Indonesia. Anak keduanya, putri, masih SMA di Surabaya.
Ternyata, menurut beliau, saya sangat kekurangan vitamin D.
Aneh. Benar-benar aneh. Setiap hari saya olahraga satu jam. Di lapangan terbuka. Kok kekurangan vitamin D.
Tapi saya tidak bisa protes. Hasil test: vitamin D saya hanya 23,4. Padahal setidaknya, harus di atas 40. Antara 40 sampai 100. Berarti vitamin D saya ini rendah sekali.
Itulah sebabnya saya diberi vitamin D (tablet) 5.000.
Mengapa tidak sekalian 10.000?
“Kalau ketinggian nanti kasihan ginjal. Untuk memberi obat, dokter harus mempertimbangkan banyak hal,” ujar dokter Hanny.
Di samping itu di Indonesia tidak dijual vitamin D di atas 5.000. “Di Singapura ada. Bahkan ada yang sampai 20.000,” katanya.
Di Indonesia kalau memberi vitamin D 10.000 harus lewat suntikan. Kalau di Singapura suntikan bisa sampai 20.000. Bahkan 100.000.
Dokter Hanny lantas seperti menyindir saya. “Banyak yang berolahraga di bawah matahari tapi pakai topi dan kaus lengan panjang,” katanya.
Ha…ha…ha… Itu saya!
Alasan resmi saya: saya tidak boleh banyak terkena sinar matahari langsung. Itu terkait dengan obat transplant yang saya minum.
Alasan tidak resminya: takut menjadi lebih item!
Pokoknya: saya salah.
Dokter Hanny begitu serius membahas vitamin D ini. Saya menjadi seperti mahasiswanya: mendengarkan dengan baik. Agar bisa menulis dengan benar.
“Dulu, vitamin D itu kita kira hanya terkait dengan tulang. Ya kan?” katanya.
Tentu saya mengangguk. Pura-pura mengerti. Tapi saya memang pernah mendengar ilmu seperti itu.
“Belakangan vitamin D itu ternyata terkait dengan TBC, pernapasan dan bahkan kanker tertentu,” katanya. Karena itu di masa Covid-19 ini vitamin D menjadi sangat penting.
Sejak kapan ilmu baru itu diketahui? 10 tahun terakhir?
“Ya, sekitar itu,” katanya.
Dokter Hanny pun pernah streaming dengan India. Di masa Covid ini. Di sana banyak ditemukan kasus hubungan vitamin D dengan TBC dan gangguan pernapasan.
Begitu asyiknya membahas vitamin D saya hampir lupa bertanya soal stetoskop yang ia pakai. Kok di tengah selangnya seperti ada power bank ukuran lontong.
“Ini baru dipakai sejak ada Covid-19,” jawabnya. Made in China.
Yang seperti power bank itu adalah booster suara. Agar suara paru-paru terdengar jelas.

Sejak Covid-19 dokter harus mengenakan APD. Telinganya pun tertutup. Padahal dengan stetoskop biasa, ujungnya harus masuk telinga. Tidak mungkin lagi seperti itu. Tidak bisa buka-tutup APD setiap visite. Juga berbahaya.
Maka kini dokter mengenakan headset. Seperti penyiar radio. Suara stetoskop didengar lewat headset itu. Dengan demikian suara paru-paru tetap terdengar jelas. “Tapi baterainya cepat habis,” katanya.
Penyakit baru memang bisa melahirkan bisnis baru. Bagi yang bakat bisnis.(*)