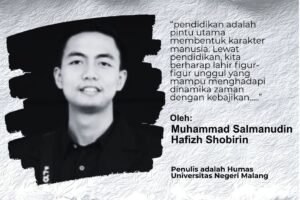Akhir-akhir ini, Prancis sedang dihebohkan dengan pembunuhan seorang guru sejarah bernama Samuel Paty oleh warga etnis Ceko beragama Islam di daerah sub urban Paris, Prancis. Guru tersebut, menurut kesaksian warga setempat, dipenggal di tengah jalan setelah menunjukkan karikatur Nabi Muhammad kepada murid-muridnya. Pihak kepolisian Prancis kemudian menembak pelaku tak lama setelah pelaku melakukan aksi biadabnya serta mengunggahnya ke media sosial. Mendengar kejadian tersebut, masyarakat Prancis geram dan menunjukkan solidaritas kepada korban dengan berkumpul di pusat Kota Paris. Mereka menyebut nama korban sembari menuntut agar prinsip kebebasan berpendapat dapat dilaksanakan. Gelombang aksi solidaritas bertajuk JeSuisSamuel (Saya Samuel) pun berlangsung hingga beberapa hari, merebak ke berbagai kota, hingga menjadi berita utama di media internasional.
Sayang, aksi tersebut dibarengi dengan kemunculan sentimen terhadap nilai keagamaan tertentu. Dalam satu kesempatan, Presiden Emanuel Macron sempat menyebut bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh “Teroris Islam”. Ia juga mengatakan akan memerangi “Islamisme Radikal” dan segera menerbitkan aturan untuk melawan “separatisme Islam”.
Pernyataan tersebut tentu saja memantik kemarahan bagi umat muslim di seluruh dunia. Terlepas dari upaya Pemerintah Prancis untuk memerangi terorisme yang tengah menyeruak beberapa tahun terakhir di Prancis, dilekatkannya peristiwa kemanusiaan dengan label identitas hanya akan memunculkan ketegangan baru. Buah pernyataan tersebut, berbagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, diantaranya negara-negara timur tengah, Turki, dan Indonesia, secara resmi mengutuk pernyataan Presiden Macron. Sedangkan masyarakat muslim di seluruh dunia kini mulai melancarkan aksi boikot terhadap produk-produk Prancis.
Merefleksikan serangkaian ketegangan tersebut, kini kita menjadi paham pentingnya toleransi dan betapa makna toleransi harus mulai direkontruksi. Toleransi dewasa ini, suka atau tidak suka, masih ditetapkan berdasarkan standar moral yang berlaku dalam mayoritas masyarakat. Ketika menjadi bagian dari mayoritas, kita mungkin secara tidak sadar pernah memaksakan nilai yang kita anut kepada masyarakat yang berbeda keyakinan dengan kita. Sedangkan ketika kita menjadi minoritas, mau tidak mau, kita harus menerima apapun nilai yang ditetapkan oleh kelompok mayoritas. Pemaknaan problematik terhadap toleransi inilah yang menjadi akar ketegangan, tidak hanya di antara Prancis dengan dunia Islam, namun juga di tengah keberagaman secara universal.
Pelajaran Untuk Indonesia
Kasus kemanusiaan yang melibatkan hubungan asimetris antara mayoritas dan minoritas
sebenarnya bukan hal baru. Tidak hanya di Prancis, kejadian serupa juga terjadi di tanah air. Kita mungkin sering mendengar bagaimana -diakui ataupun tidak- sekelompok pihak memaksakan kehendak dan nilai-nilai yang dianutnya terhadap kelompok lain yang memiliki keyakinan berbeda. Pemaksaan kehendak tersebut seringkali bermuara pada kejadian yang melibatkan kekerasan, aksi anarkis, hingga pembunuhan. Contohnya, kita mengetahui di Indonesia masih sering terjadi perusakan rumah ibadah umat agama tertentu. Lebih dari itu, kita juga sering mendengar pengusiran terhadap ras tau suku tertentu, beberapa kejadian bahkan terjadi di Malang Raya. Sekalipun pemerintah dan tokoh masyarakat mengampanyekan toleransi, ketegangan tetap terjadi di masyarakat ketika terjadi pertemuan antara dua atau lebih keyakinan berbeda.
Kejadian-kejadian tersebut agaknya dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Pertama, bahwa status mayoritas ataupun minoritas bukanlah hal yang absolut. Terkadang, kita dapat menjadi mayoritas di suatu wilayah, namun menjadi minoritas di wilayah lain. Oleh karenanya, memaksakan nilai toleransi berdasarkan status mayoritas dan minoritas, seperti yang tengah dilakukan Prancis maupun negara mayoritas muslim di seluruh dunia, hanya akan menghasilkan ketegangan-ketegangan baru.
Kedua, bahwa kasus kemanusiaan harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Tidak hanya dari kaca mata pelaku maupun korban, namun juga dari perspektif nilai dan budaya yang menyertainya. Semisal, ketika kita melihat seorang guru yang menunjukkan karikatur tak senonoh dari tokoh agama kepada publik, maka tentu kita harus melihat nilai dan budaya yang berlaku di masyarakat. Di Prancis yang menganut nilai kebebasan berekspresi dan sekulerisme, hal tersebut tentu saja dibenarkan. Sedangkan ketika kita melihat kejadian serupa di Indonesia yang menganut nilai-nilai ketuhanan dan budaya ketimuran, kejadian tersebut tentu saja dapat dipandang sebagai tindak pidana. Tidak hanya status mayoritas dan minoritas, nilai dan budaya juga merupakan sesuatu yang relatif. Oleh karenanya, tidak elok rasanya untuk memaksakan nilai dan budaya terhadap masyarakat yang menganut keyakinan berbeda.
Mengingat Ulang Prinsip Kemanusiaan Gus Dur
Salah satu tokoh bangsa yang memberikan sumbangsih pemikiran tentang kemanusiaan adalah Abdurrahman Wahid atau biasa dipanggil sebagai Gus Dur. Presiden keempat Republik Indonesia tersebut kerap kali diingat karena guyonan-guyonannya. Namun, tak kalah penting untuk diingat, adalah bagaimana Gus Dur selalu konsisten dalam membela kaum minoritas di berbagai kesempatan. Contoh paling populer antara lain ketika Gus Dur mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 ketika menjabat sebagai Presiden. Berkat kebijakan tersebut, kaum Tionghoa dan Konghucu dapat melaksanakan keyakinan serta merayakan hari rayanya di ruang publik.
Kita tentu mengingat bagaimana kejadian tahun 1965 menyisakan luka yang sangat dalam bagi bangsa ini. Namun, alih-alih menggunakan status mayoritas untuk memaksakan nilai yang dianutnya, Gus Dur justru mendekati dan mengadvokasi hak-hak pihak yang menjadi minoritas dalam peristiwa tersebut. Kebesaran hati, empati, dan kesadaran untuk melindungi minoritas inilah yang menurut saya harus ditanamkan oleh generasi penerus bangsa, apabila kita ingin hidup dalam kerangka masyarakat yang majemuk. Karena bangsa ini terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama, maka kemajemukan adalah suatu keniscayaan. Belajar dari kejadian di Prancis, melabeli suatu peristiwa kemanusiaan dengan identitas bukanlah jalan keluar dari suatu masalah.
Sebaliknya, kita perlu menumbuhkan kepekaan bahwa status sosial dan nilai yang kita anut adalah sesuatu yang relatif. Maka dari itu, sembari memiliki kemewahan untuk menjadi mayoritas, kita harus menumbuhkan empati kepada mereka yang menjadi minoritas.

UI)